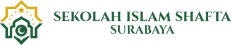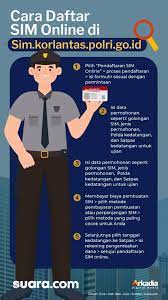Pada awal abad ke-19, Belanda menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah. Negara itu baru saja melewati perang besar seperti Perang Jawa (1825–1830) dan kehilangan wilayah Belgia pada 1830. Untuk menyelamatkan keuangannya, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda, yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, menerapkan sebuah sistem baru yang dikenal sebagai cultuurstelsel atau tanam paksa. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830.
Dalam sistem ini, setiap desa diwajibkan menyerahkan sebagian tanahnya, sekitar seperlima dari total luas, untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan rempah-rempah. Tanaman tersebut menjadi komoditas yang menguntungkan di pasar internasional. Tidak hanya menyerahkan tanah, para petani juga harus bekerja tanpa bayaran di lahan-lahan tersebut selama waktu tertentu. Pemerintah kolonial menetapkan harga yang sangat rendah untuk hasil panen mereka, sehingga keuntungan besar sepenuhnya dinikmati oleh Belanda.
Pada awalnya, pemerintah kolonial berhasil memaksa masyarakat untuk mengikuti sistem ini dengan berbagai cara, termasuk melalui tekanan para penguasa lokal seperti bupati dan kepala desa. Para petani tidak punya pilihan selain patuh, karena penolakan berarti hukuman berat. Namun, seiring berjalannya waktu, efek sistem tanam paksa ini mulai terasa. Tanah-tanah subur yang biasanya digunakan untuk menanam padi dan kebutuhan pangan lain terpaksa diganti dengan tanaman ekspor. Akibatnya, banyak daerah mengalami kelangkaan pangan yang menyebabkan kelaparan besar, seperti yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 1840-an.
Sementara itu, di sisi lain dunia, Belanda menikmati kemakmuran yang luar biasa. Pendapatan dari hasil tanam paksa mengalir deras ke kas negara, membantu menyelamatkan ekonomi Belanda yang nyaris bangkrut. Bagi pemerintah kolonial, sistem ini dianggap sebagai solusi sempurna. Namun, di balik keberhasilan tersebut, penderitaan rakyat pribumi terus bertambah. Para petani menderita bukan hanya secara fisik tetapi juga mental akibat kerja paksa yang berat dan kondisi kehidupan yang semakin sulit.
Lama-kelamaan, kritik terhadap tanam paksa mulai bermunculan, baik dari dalam Belanda maupun luar negeri. Salah satu suara paling lantang datang dari Eduard Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang pernah bertugas di Hindia Belanda. Melalui novelnya yang terkenal, Max Havelaar (1860), ia membuka mata dunia tentang ketidakadilan dan penderitaan yang dialami rakyat pribumi. Buku ini menggugah hati banyak orang di Belanda dan memicu perdebatan besar tentang moralitas sistem kolonial.
Tekanan politik dan opini publik akhirnya membuat pemerintah Belanda mulai mengurangi praktik tanam paksa pada pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1870, diterapkan reformasi agraria melalui Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet), yang menghentikan sistem tanam paksa secara resmi. Tanah-tanah mulai disewakan kepada perusahaan swasta, menandai peralihan ekonomi kolonial ke model berbasis perkebunan swasta.
Namun, jejak cultuurstelsel tetap terasa lama setelah sistem ini dihapuskan. Tanam paksa meninggalkan luka mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia, simbol dari eksploitasi dan ketidakadilan yang dilakukan kolonialisme. Sistem ini mengajarkan kita betapa pentingnya memperjuangkan keadilan dan kedaulatan bangsa. Melalui cerita sejarah ini, generasi masa kini dapat memahami perjuangan leluhur mereka dan pentingnya menghargai kemerdekaan yang telah diperoleh dengan pengorbanan besar.