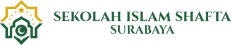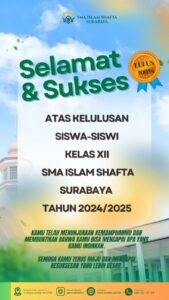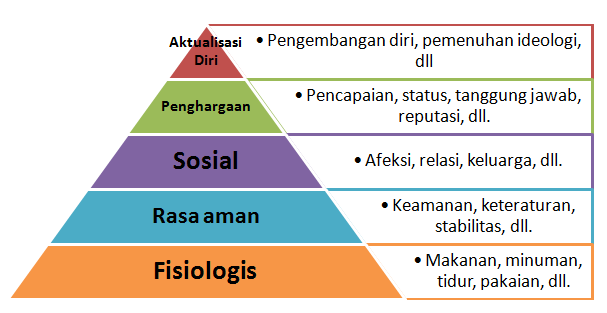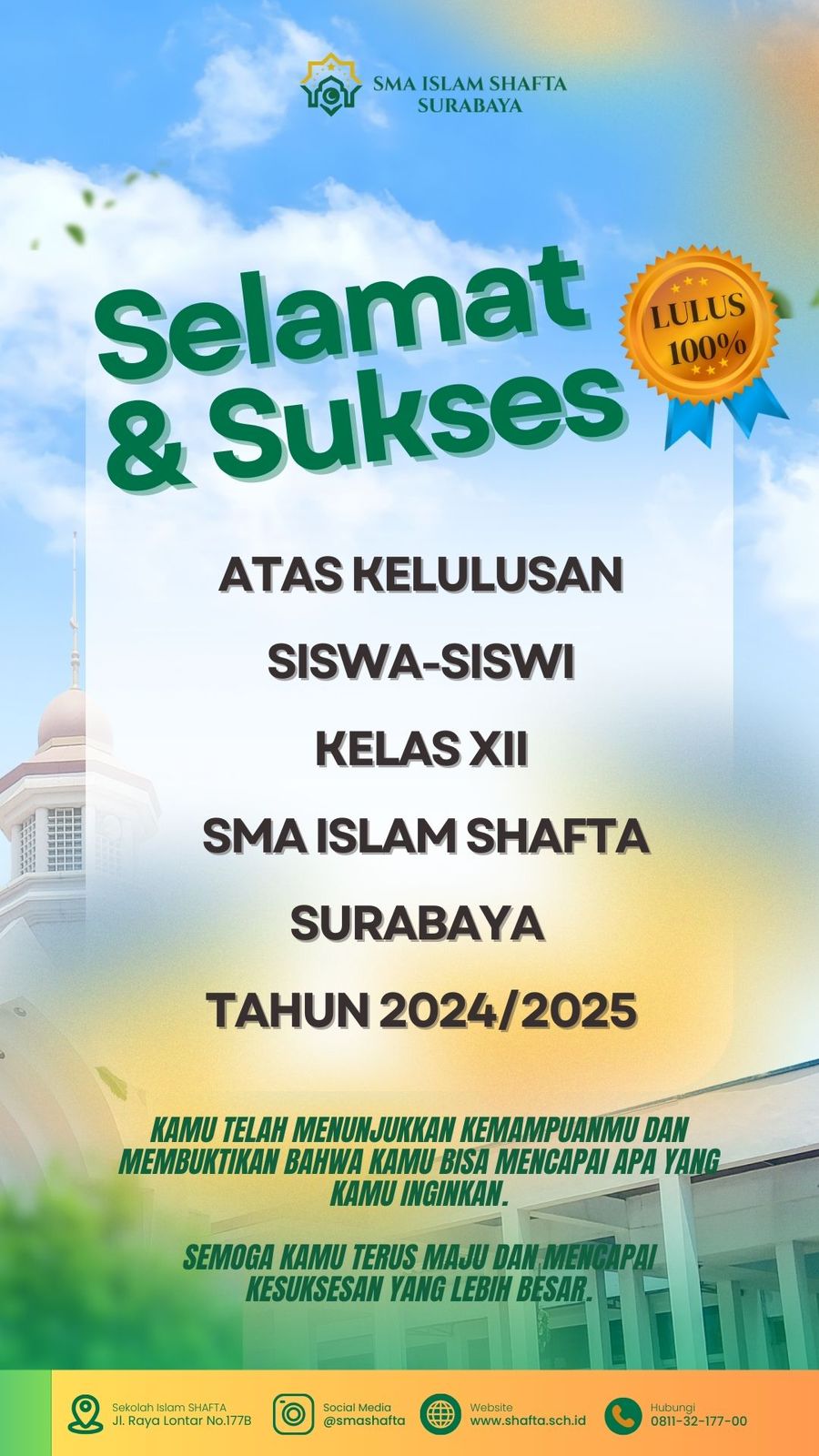Mustafik, sejarah wajib
perbandingan zaman praaksara dan zaman sejarah
A. Istilah Pra Sejarah, Pra Aksara dan Nirleka Pra-sejarah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di saat catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Tidak jauh berbeda dengan istilah praaksara yang berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa pra-sejarah dan pra-aksara disebut juga dengan masa nirleka (nir artinya tidak ada, dan leka artinya tulisan), yaitu masa tidak ada tulisan. 1 Masa pra-aksara disebut juga dengan masa pra-sejarah, yaitu suatu masa dimana manusia belum mengenal tulisan. Adapun masa sesudah manusia mengenal tulisan disebut juga dengan masa aksara atau masa sejarah. Mengenai istilah, terdapat pendapat bahwa istilah pra-aksara sebenarnya lebih tepat karena pra-aksara berarti sebelum ada tulisan. Berbeda dengan pra sejarah yang berarti sebelum ada sejarah. Meski manusia belum mengenal tulisan, tidak berarti manusia tidak memiliki sejarah dan kebudayaan. Seperti diungkapkan Colin Renfrew, zaman pra-sejarah dapat dikatakan permulaan terbentuknya alam semesta, namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di saat kehidupan manusia di Bumi yang belum mengenal tulisan.2 Batas antara zaman pra-sejarah dengan zaman sejarah adalah mulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa pra-sejarah adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, sedangkan sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan. Berakhirnya zaman pra-sejarah atau dimulainya zaman sejarah untuk setiap bangsa di dunia tidak sama tergantung dari 1 R. Sukmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I, (Jakarta: Kanisius, 1990), hlm.1. 2 Renfrew & Bahn, “Where? Survey and Excavation of Sites and Features”, dalam Archaeology: Theories, Methods and Practice (5th ed.), (London: Thames & Hudson, 2008), hlm.6. peradaban bangsa tersebut. Contohnya, Bangsa Mesir sekitar tahun 4000 SM masyarakatnya sudah mengenal tulisan, sehingga pada saat itu, Bangsa Mesir sudah memasuki zaman sejarah. Berbeda dengan zaman pra-sejarah di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti berbentuk yupa yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur baru memasuki era sejarah. Gambar 1.1. Yupa, Tonggak Bangsa Indonesia Memasuki Zaman Sejarah Sumber: diolah dari R. Sukmono, 1990. Zaman pra sejarah ini adalah zaman yang paling sulit di temukan bukti sejarahnya. Karena tidak terdapat peninggalan catatan tertulis dari zaman prasejarah. Keterangan mengenai zaman ini diperoleh melalui bidang-bidang ilmu seperti Paleontologi, Astronomi, Biologi, Geologi, Antropologi, Arkeologi. Dalam artian bahwa bukti-bukti pra-sejarah didapat dari artefak-artefak yang ditemukan di daerah penggalian situs pra-sejarah. B. Arkeologi dan Penelitian Prasejarah Indonesia Arkeologi, berasal dari bahasa Yunani, archaeo yang berarti "kuna" dan logos, berarti "ilmu". Nama alternatif Arkeologi adalah ilmu sejarah kebudayaan material. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan (manusia) masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Kajian sistematis meliputi penemuan, dokumentasi, analisis, dan interpretasi data berupa artefak (budaya bendawi, seperti kapak batu dan bangunan candi) dan ekofak (benda lingkungan, seperti batuan, rupa muka bumi, dan fosil) maupun fitur (artefaktual yang tidak dapat dilepaskan dari tempatnya (situs arkeologi). Teknik penelitian yang khas adalah penggalian (ekskavasi) arkeologis, meskipun survei juga mendapatkan porsi besar.3 Tujuan Arkeologi beragam dan menjadi perdebatan yang panjang. Diantaranya adalah yang disebut dengan paradigma Arkeologi, yaitu menyusun sejarah kebudayaan, memahami perilaku manusia, serta mengerti proses perubahan budaya. Karena bertujuan untuk memahami budaya manusia, maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Meskipun demikian, terdapat berbagai ilmu bantu yang digunakan, antara lain Sejarah, Antropologi, Geologi (dengan ilmu tentang lapisan pembentuk bumi yang menjadi acuan relatif umur suatu temuan Arkeologis), Geografi, Arsitektur, Paleoantropologi dan Bioantropologi, Fisika (antara lain dengan Karbon C-14 untuk mendapatkan pertanggalan mutlak), ilmu Metalurgi (untuk mendapatkan unsur-unsur suatu benda logam), serta Filologi (mempelajari naskah lama).4 Arkeologi pada masa sekarang merangkum berbagai bidang yang berkait. Sebagai contoh, penemuan mayat kuno yang dikubur akan menarik minat pakar dari berbagai bidang untuk mengkaji tentang pakaian dan jenis bahan digunakan, bentuk keramik dan cara penyebaran, kepercayaan melalui apa yang dikebumikan bersama mayat tersebut, pakar kimia yang mampu menentukan usia galian melalui cara seperti metode pengukuran Karbon 14. Sementara pakar genetik yang ingin mengetahui pergerakan perpindahan manusia purba, meneliti DNA-nya. Secara khusus, Arkeologi mempelajari budaya masa silam, yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah (sebelum dikenal tulisan), maupun 3 G. A. Wagner, Age Determination of Young Rocks and Artifacts: Physical and Chemical Clocks in Quaternary Geology and Archaeology, (Berlin: Springer, 1998), hlm.12. 4 Ibid. pada masa sejarah (ketika terdapat bukti-bukti tertulis). Pada perkemba- ngannya, Arkeologi juga dapat mempelajari budaya masa kini, sebagaimana dipopulerkan dalam kajian budaya bendawi modern (modern material culture). Karena bergantung pada benda-benda peninggalan masa lalu, maka Arkeologi sangat membutuhkan kelestarian benda-benda tersebut sebagai sumber data. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan disiplin lain, yaitu Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi (Archaeological Resources Management), atau lebih luas lagi adalah disiplin ilmu Pengelolaan Sumberdaya Budaya (Culture Resources Management). 5 Perkembangan Arkeologi di Indonesia, dimulai dari lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan, seperti Bataviaashe Genootshcap van Kunsten en Wettenschappen di Jakarta yang kemudian merintis pendirian museum tertua, sekarang menjadi Museum Nasional. Lembaga pemerintah pada masa kolonial yang bergerak di bidang Arkeologi adalah Oudheidkundige Dienst yang banyak membuat survei dan pemugaran atas bangunan- bangunan purbakala terutama candi. Pada masa kemerdekaan, lembaga tersebut menjadi Dinas Purbakala hingga berkembang sekarang menjadi berbagai lembaga seperti Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Balai Arkeologi yang tersebar di daerah-daerah dan Direktorat Purbakala serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional di Jakarta. Disamping itu, terdapat beberapa perguruan tinggi yang membuka Jurusan Arkeologi untuk mendidik tenaga sarjana di bidang Arkeologi.6 Perguruan-perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Indonesia (Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya), Universitas Gadjah Mada (Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya), Universitas Hasanuddin (Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra), dan Universitas Udayana (Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra). Ahli arkeologi Indonesia, yang umumnya 5 Robert J. Sharer & Wendy Ashmore, Archaeology: Discovering Our Past, (California: Mayfield Publishing Company, 1993), hlm 8; Y. Rowan & U. Baram, Marketing Heritage: Archaeology and the Consumption of the Past, (Walnut Creek CA: Altanira Press, 2004), hlm.3. 6 Edi Sedyawati, Suggestion for Future Global Strategy in Indonesian Archeology, (Jakarta: UI, 2001), hlm.12; J. Pardosi, “Potensi Arkeologi Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya”, dalam Berkala Arkeologi Sangkhakala No. 14/2004 November 2004, Balai Arkeologi Medan, hlm: 27-35. merupakan lulusan dari keempat perguruan tinggi tersebut, berhimpun dalam Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Tokoh-tokoh Arkeologi Indonesia terkenal antara lain R. Soekmono yang mengepalai pemugaran Candi Borobudur, dan R. P. Soedjono, pendiri dan Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia pertama dan mantan Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Gambar 1.2. Aktivitas Penggalian Purbakala di Indonesia sumber: diolah dari R. Sukmono, 1990. Disiplin Arkeologi Indonesia masih secara kuat diwarnai dengan adanya pembagian kronologis, yaitu periode Prasejarah, Klasik (Hindu- Buddha), Islam, serta Kolonial. Oleh karena itu, dalam Arkeologi Indonesia dikenal spesialisasi menurut periode tersebut. Keistimewaan Arkeologi Indonesia adalah masuknya disiplin Epigrafi, yang menekuni pembacaan prasasti kuna. Pada perkembangannya terdapat minat-minat khusus seperti Etnoarkeologi, Arkeologi Bawah Air dan Arkeometri. Terdapat pula sub-disiplin yang berkem-bang karena persinggungan dengan ilmu lain, seperti Arkeologi Lingkungan atau Arkeologi Ekologi, Arkeologi Ekonomi, Arkeologi Seni, Arkeologi Demografi, dan Arkeologi Arsitektur.7 7 D.W. Ramelan, “Permasalahan Pengelolaan Cagar Budaya dan Kajian Manajemen Sumber Daya Arkeologi”, makalah Pertemuan Ilimiah Arkeologi-VII, Maret 1996. C. Perkembangan Penelitian Prasejarah Indonesia Penelitian tentang prasejarah Indoensia telah berlangsung lama. Sejak zaman Hindia Belanda upaya penelitian untuk menguak masa lalu bangsa- bangsa telah dilakukan terutama oleh pakar dari luar negeri (Belanda) seperti Eugene Dubois, Von Koenigswald, Van Heekeren, dan lain-lain. Mereka melakukan penelitian untuk merekonstuksi pra-sejarah di Indonesia. Peneliti- an yang dilakukan menunjukkan hasil yang luar biasa yang dapat dilihat dari penemuan-penemuan yang hebat yaitu penemuan situs di berbagai tempat seperti Situs Sangiran di Jawa Tengah, Situs Pati Ayam, Situs Sambung Macan, dan lain-lain. Disamping itu penelitianpenelitian para Arkelolog ini juga menghasilkan temuan yang mencengangkan dunia yaitu penemuan fosil manusia pra-sejarah Indonesia.8 Setelah zaman kemerdekaan sarjana dari Indonesia juga telibat aktif dalam penelitian pra-sejarah. Berkembangnya perguruan tinggi di Indonesia khususnya untuk bidang Arkelogi menyebabkan banyak dihasilkan Arkeolog yang berkompeten dari Indonesia. Ahli palaeontologi Indonesia, Teuku Yacoeb (UGM) telah melakukan banyak penelitian yang mahahebat, disamping masih ada tokoh lain seperti RP Sujono yang juga telah melakukan banyak penelitian di bidang Palaeontologi. Selain itu ada juga ahli luar negeri yang meneliti prasejarah Indonesia seperti Peter Bellwood yang meneliti prasejarah di Asia Tenggara. 9 D. Sumber-sumber Prasejarah Indonesia 1. Artefak Artefact atau artefak adalah semua benda yang telah diubah sebagian atau seluruh bagiannya untuk kepentingan manusia. Contoh artefak adalah kapak batu, arca dewa, naskah. Artefak atau artifact merupakan benda Arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, 8 F.A. Wagner, Indonesian the Art of an Island Group, (Netherland: Biljage D. 1962, hlm.8. 9 Daud Aris Tanudirjo, “Ragam Metode Penelitian Arkeologi Dalam Skripsi Karya Mahasiswa Arkeologi UGM”, Laporan Penelitian, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, 1988., hlm.2; lihat juga Peter Bellwood, Prasejarah Kepulauan Indo- Malaysia, (Jakarta: Pustaka, 2000). 7 yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempeng dan kertas, senjata-senjata logam (anak panah, mata panah, dll), terracotta dan tanduk binatang. barang yang bersejarah ini penting untuk diletakkan di museum sehingga semua orang dapat melihat dan mempelajarinya.10 Artefak dalam Arkeologi mengandung pengertian benda (atau bahan alam) yang jelas dibuat oleh (tangan) manusia atau jelas menam- pakkan (observable) adanya jejak-jejak buatan manusia padanya (bukan benda alamiah semata) melalui teknologi pengurangan maupun teknologi penam-bahan pada benda alam tersebut. Ciri penting dalam konsep artefak adalah bahwa benda ini dapat bergerak atau dapat dipindahkan (movable) tangan manusia dengan mudah (relatif) tanpa merusak atau menghancurkan bentuknya. Gambar 1.3. Contoh Artefak Sumber: diolah dari R. Sukmono, 1990. 10 Ayatrohaedi, et al, Kamus Istilah Arkeologi I, (Jakarta: Pusat Pembinan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm.9; Didier Colin, Dictionary of Symbols, Myths, and Legends, (Hachette, 2000), hlm. 21; Irwan Suryanegara, et al, “Artefak Purba Pasemah: Analisis Ungkap Rupa Patung Megalitik di Pasemah”, Jurnal ITB Vol. 1 No. 1. tahun 2007, hlm.1; Kusnadi, et.al., Sejarah Seni Rupa Indonesia, (Jakarta: Depdikbud, 1979), hlm. 12. 8 2. Fitur/Feature Feature adalah gejala atau pertanda sisa aktivitas manusia meskipun tidak dapat dipindahkan kecuali membongkar dudukan atau matriks-nya. Contoh fitur adalah lubang sampah, candi, gereja. 11 Gambar 1.4. Contoh Fitur Sumber: diolah dari R. Sukmono, 1990. 3. Fosil Fossil atau dalam bahasa Latin, fossa yang berarti "menggali keluar dari dalam tanah") adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral.12 Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Oleh para pakar dibedakan beberapa macam fosil. Ada fosil batu biasa, fosil yang terbentuk dalam batu ambar, fosil ter, seperti yang terbentuk di sumur ter La Brea di Kalifornia. Hewan atau tumbuhan yang dikira sudah punah tetapi ternyata masih ada disebut fosil hidup. Fosil yang paling umum adalah kerangka 11 van der Hoop, Megalithic Remains in South-Sumatra, translated by William Shirlaw, (Netherland: W.J. Thieme & Cie Zutphen, 1932) hlm. 8. 12 Kelly & Thomas, Archaeology: Down To Earth (4th ed.), (Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning, 2001), hlm. 18. 9 yang tersisa seperti cangkang, gigi dan tulang. Fosil jaringan lunak sangat jarang ditemukan. 13 Gambar 1.5. Contoh Fosil Sumber: diolah dari Yulius Yunus, 1990. 4. Biofact Atau Ecofact Biofact atau ecofact adalah semua benda yang tidak pernah diubah oleh manusia, tetapi menjadi bagian dari kehidupan manusia.14 Contoh ekofak adalah fosil tulang gajah purba, tulang sisa makanan, jaringan sungai. Dalam Arkeologi, ekofak atau dikenal pula dengan nama biofak merupakan obyek yang ditemukan pada situs Arkeologi dan memiliki signifikansi Arkeologis, tetapi benda tersebut tidak pernah memiliki perubahan yang dilakukan oleh manusia. Obyek ini terkait dengan lingku- ngan, seperti tanduk hewan, arang, tanaman, dan polen. Ekofak merupakan obyek alami yang biasanya terkait dengan temuan artefak dan fitur. Ekofak memperlihatkan bagaimana manusia pada masa lampau beradaptasi terhadap lingkungannya. 13 Yulius Yunus, Seni Rupa Prasejarah Eropa, (Bandung: FPBS-Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), 1970), hlm. 21. 14 Ayatrohaedi, et al, op.cit., hlm.22; lihat juga tulisan P. Boylan, “Ecomuseums and the New Museology”, Museums Journal, no. 92, hlm. 29-30.; P. S. Brahmana, "Kebudayaan di Indonesia Dari Sisi Ide dan material", dalam Studia Cultura, Jurnal Ilmiah Ilmu Budaya, tahun I no. 1. 2002., hlm.1. 10 Gambar 1.6. Contoh Ekofak Tulang Gajah Purba Sumber: diolah dari Yulius Yunus, 1990. Jenis ekofak yang umum ditemukan adalah sisa-sisa tanaman atau pollen, yang sering disebut juga sebagai botani makro, dapat memberikan berbagai macam informasi dari pola makan hingga obat dan tekstil. Pollen memberikan informasi bagi Arkeolog mengenai lingkungan pada masa lampau, dan makanan yang diproses atau ditanam oleh masyarakat pada masa tersebut. Pollen juga dapat memberi tahu mengenai perubahan lingkungan dan pola makan. Ekofak lainnya, seperti biji, dapat memberi tahu Arkeolog mengenai spesies tanaman yang dipergunakan pada masa lampau. Jika biji tersebut terdapat dalam jumlah yang banyak pada suatu situs, dapat diambil kesimpulan bahwa spesies tanaman tersebut ditanam atau dikembangkan untuk makanan atau benda lainnya yang berguna untuk manusia, seperti pakaian, atau bahkan benda persembahan.15 Tipe ekofak lainnya adalah kayu. Kayu terbuat dari selulosa, karbohidrat, dan lignin. Pada temuan batang kayu, dapat dilihat berapa umur sisa pohon tersebut dari cincin yang terdapat pada tubuh pohon, 15 Gregorius Dwi. Kuswanto, “Eksploitasi Sumberdaya Akuatik oleh Komunitas Penghuni Song Jrebeng, Gunung Kidul: Kajian Lingkungan dan Ekofak Organik”, Skripsi Sarjana, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2007), hlm.1; lihat juga Puslitarkenas, Metode Penelitian Arkeologi, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengemba- ngan Arkeologi Nasional, 2008), hlm.4. 11 sehingga dapat dilakukan penanggalan dedrokronologi. 16 Arang adalah kayu yang terbakar, dimana biasa ditemukan pada situs gua. Arang ini dapat diketahui penanggalannya dengan menggunakan Carbon-1417, sehingga dapat memberikan informasi mengenai lingkungan di sekitarnya.